Salah satu aspek yang dilihat saat menilai kualitas kamera digital
adalah sensornya. Kita tahu sensor pada kamera digital adalah rangkaian
peka cahaya, tempat gambar dibentuk dan dirubah menjadi sinyal data.
Tidak semua kamera digital punya ukuran sensor yang sama. Sesuai
bentuknya, kamera digital yang kecil umumnya pakai sensor yang juga
kecil, sedangkan kamera mirrorless dan DSLR memakai sensor yang lebih besar. Sensor dengan luas penampang sama dengan ukuran film 35mm disebut sensor full frame.
Mengapa
penting untuk mengenal ukuran sensor di kamera digital? Karena ukuran
sensor berkaitan dengan kemampuan menangkap cahaya dan menentukan bagus
tidaknya hasil foto yang diambil. Sekeping sensor pada dasarnya
merupakan sekumpulan piksel yang peka cahaya, saat ini umumnya sekeping
sensor punya 10 juta piksel bahkan lebih. Makin banyak piksel, makin
detil foto yang bisa direkam. Tapi saat bicara kualitas hasil foto, kita
perlu mencari lebih jauh info ukuran sensornya, bukan sekedar berapa
juta pikselnya saja.
Megapiksel, atau resolusi sensor, saat ini seperti jadi cara efektif
untuk marketing. Maka itu ponsel berkamera pun dibuat punya sensor yang
megapikselnya tinggi. Pun demikian dengan kamera saku sampai kamera
canggih, semua berlomba menjual ‘megapiksel’ ini. Bayangkan sensor kecil
yang dijejali piksel begitu banyak, seperti apa rapat dan sempitnya
piksel-piksel itu berhimpit? Dibawah ini adalah contoh ilustrasi ukuran
sensor, dua di sebelah kiri (yang berwarna merah) adalah mewakili sensor
kecil, umumnya ditemui di kamera saku. Sensor kecil memang murah dalam
hal biaya produksi, dan bisa membuat bentuk kamera jadi sangat kecil.
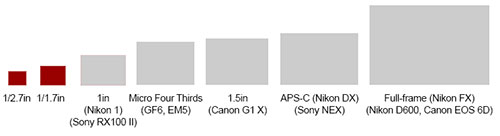
Di sisi lain, ukuran sensor yang lebih besar memang lebih mahal dan
kamera/lensanya jadi lebih besar. Tapi keuntungannya dengan luas
penampang yang lebih besar, tiap piksel punya ukuran yang lebih besar
dan mampu menangkap cahaya dengan lebih baik. Maka itu saat kondisi
kurang cahaya, dimana kamera tentu akan menaikkan ISO (kepekaan sensor),
yang terjadi adalah hasil foto dari kamera dengan sensor besar punya
hasil foto yang lebih baik. Sedangkan di ISO tinggi, kamera sensor kecil
akan dipenuhi bercak noise yang mengganggu. Noise ini oleh kamera
modern dicoba untuk dikurangi secara otomatis (lewat prosesor kamera)
namun yang terjadi hasil fotonya jadi tidak natural seperti lukisan cat
air.
Sensor CMOS vs sensor CCD
Perbedaan utama desain CMOS dan CCD adalah pada sirkuit digitalnya.
Setiap piksel pada sensor CMOS sudah memakai sistem chip yang langsung
mengkonversi tegangan menjadi data, sementara piksel-piksel pada sensor
CCD hanya berupa photodioda yang mengeluarkan sinyal analog (sehingga
perlu rangkaian terpisah untuk merubah dari analog ke digital/ADC). Anda
mungkin penasaran mengapa banyak produsen yang kini beralih ke sensor
CMOS, padahal secara hasil foto sensor CCD juga sudah memenuhi standar.
Alasan utamanya menurut saya adalah soal kepraktisan, dimana sekeping
sensor CMOS sudah mampu memberi keluaran data digital siap olah sehingga
meniadakan biaya untuk membuat rangkaian ADC.
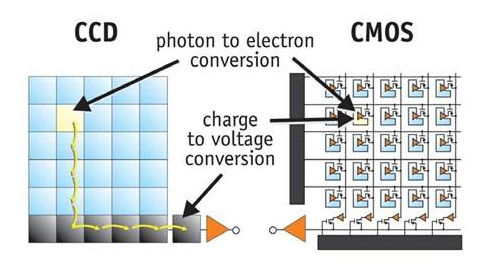
Selain itu sensor CMOS juga punya kemampuan untuk diajak bekerja
cepat yaitu sanggup mengambil banyak foto dalam waktu satu detik. Ini
tentu menguntungkan bagi produsen yang ingin menjual fitur high speed burst. Faktor
lain yang juga perlu dicatat adalah sensor CMOS lebih hemat energi
sehingga pemakaian baterai lebih awet. Maka itu tak heran kini semakin
banyak kamera digital (DSLR maupun kamera saku) yang akhirnya beralih ke
sensor CMOS. Adapun soal kemampuan sensor CMOS dalam ISO tinggi pada
dasarnya tak berbeda dengan sensor CCD dimana noise yang ditimbulkan
juga linier dengan kenaikan ISO. Kalau ada klaim sensor CMOS lebih aman
dari noise maka itu hanya kecerdikan produsen dalam mengatur noise reduction.
Cara sensor ‘menangkap’ warna
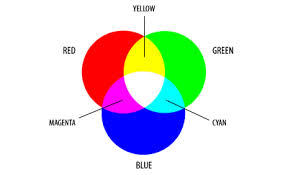
Sensor gambar pada dasarnya
merupakan perpaduan dari chip peka cahaya (untuk mendapat informasi
terang gelap) dan filter warna (untuk merekam warna seakurat mungkin).
Di era fotografi film, pada sebuah roll film terdapat
tiga lapis emulsi yang peka terhadap warna merah (Red), hijau (Green)
dan biru (Blue). Di era digital, sensor kamera memiliki bermacam variasi
desain teknologi filter warna tergantung produsennya dan harga sensornya.
Cara kerja filter warna cukup simpel, misal seberkas cahaya
polikromatik (multi warna) melalui filter merah, maka warna apapun
selain warna merah tidak bisa lolos melewati filter itu. Dengan begitu
sensor hanya akan menghasilkan warna merah saja. Untuk mewujudkan jutaan
kombinasi warna seperti keadaan aslinya, cukup memakai tiga warna
filter yaitu RGB (sama seperti film) dan pencampuran dari ketiga warna
komplementer itu bisa menghasilkan aneka warna yang sangat banyak. Hal
yang sama kita bisa jumpai juga di layar LCD seperti komputer atau
ponsel yang tersusun dari piksel RGB.
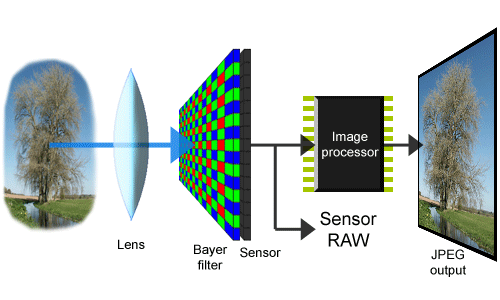
Bayer CFA
Sesuai nama penemunya yaitu Bryce Bayer, seorang ilmuwan dari Kodak
pertama kali memperkenalkan teknik ini di tahun 1970. Sensor dengan
desain Bayer Color Filter Array (CFA) termasuk sensor paling
banyak dipakai di kamera digital hingga saat ini. Keuntungan desain
sensor Bayer adalah desain mosaik filter warna yang simpel cukup satu
lapis, namun sudah mencakup tiga elemen warna dasar yaitu RGB (lihat
ilustrasi di atas). Kerugiannya adalah setiap satu piksel pada dasarnya
hanya ‘melihat’ satu warna, maka untuk bisa menampilkan warna yang
sebenarnya perlu dilakukan teknik color sampling dengan perhitungan rumit berupa interpolasi (demosaicing). Perhatikan
ilustrasi mosaik piksel di bawah ini, ternyata filter warna hijau punya
jumlah yang lebih banyak dibanding warna merah dan biru. Hal ini dibuat
mengikuti sifat mata manusia yang lebih peka terhadap warna hijau.
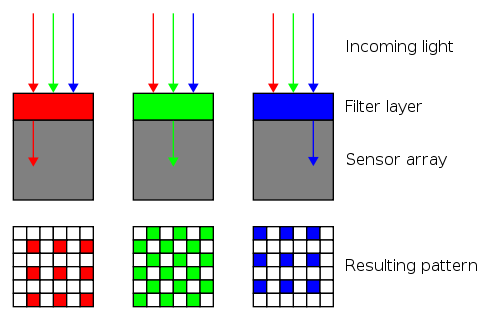
Kekurangan sensor Bayer yang paling disayangkan adalah hasil foto
yang didapat dengan cara interpolasi tidak bisa menampilkan warna sebaik
aslinya. Selain itu kerap terjadi moire pada saat sensor menangkap pola
garis yang rapat seperti motif di kemeja atau pada bangunan. Cara
termudah mengurangi moire adalah dengan memasang filter low pass yang bersifat anti aliasing, yang membuat ketajaman foto sedikit menurun.
Sensor X Trans
Sensor dengan nama X Trans dikembangkan secara ekslusif oleh Fujifilm, dan digunakan pada beberapa kamera kelas atas Fuji
seperti X-E2 dan X-T1. Desain filter warna di sensor X Trans merupakan
pengembangan dari desain Bayer yang punya kesamaan bahwa setiap piksel
hanya bisa melihat satu warna. Bedanya, Fuji menata ulang susunan filter
warna RGBnya. Bila pada desain Bayer kita menemui dua piksel hijau,
satu merah dan satu biru pada grid 2×2, maka di sensor X Trans kita akan
menemui pola grid 6×6 yang berulang. Nama X trans sepertinya diambil
dari susunan piksel hijau dalam grid 6×6 yang membentuk huruf X seperti
contoh di bawah ini.
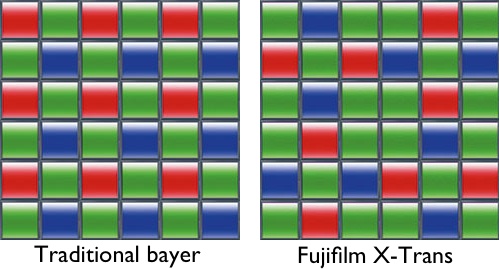
Fuji mengklaim beberapa keunggulan desain X Trans seperti :
- tidak perlu filter low pass, karena desain pikselnya sudah aman dari moire
- terhindar dari false colour, karena setiap baris piksel punya semua elemen warna RGB
- tata letak filter warna yang agak acak memberi kesan grain layaknya film
Sepintas kita bisa setuju kalau desain X Trans lebih baik daripada
Bayer, namun ada beberapa hal yang masih jadi kendala dari desain X
Trans ini, yaitu hampir tidak mungkin Fuji akan memberikan lisensi X
Trans ke produsen kamera lain (artinya hanya pemilik kamera Fuji tipe
tertentu yang bisa menikmati sensor ini). Kendala lain adalah sulitnya
dukungan aplikasi editing untuk bisa membaca file RAW dari sensor X
Trans ini.
Sensor Foveon X3
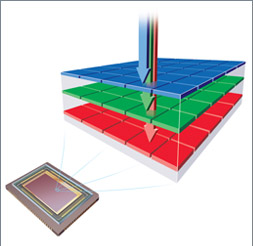
Foveon
sementara ini juga ekslusif dikembangakan untuk kamera Sigma tipe
tertentu. Dibanding sensor lain yang cuma punya satu lapis filter warna,
sensor Foveon punya tiga lapis filter warna yaitu lapisan merah, hijau dan
biru. Desain ini persis sama dengan desain emulsi warna pada roll film
foto. Hasil foto dari sensor Foveon memberikan warna yang akurat dan
cenderung vibrant, bahasa gampangnya seindah warna aslinya. Hal yang
wajar karena setiap photo detector di sensor Foveon memang menerima
informasi warna yang utuh dan tidak diperlukan lagi proses ‘menebak’
warna seperti sensor Bayer atau X-Trans.
Yang jadi polemik dalam sensor Foveon adalah jumlah piksel aktual.
Misalnya ada tiga lapis filter warna yang masing-masing berjumlah 3,4
juta piksel, maka Foveon menyebut sensornya adalah sensor 10,2 MP karena
didapat dari 3 lapis filter 3,4 MP. Ini agak rancu karena saat foto
yang dihasilkan dari sensor Foveon kita lihat ukuran pikselnya memang
hanya 2268 x 1512 piksel atau setara dengan 3,4 MP.
Salah satu kelemahan dari sensor Foveon adalah noise yang sudah
terasa mengganggu walau di ISO menengah seperti ISO 800. Tapi seiring
peningkatan teknologi pengurang noise maka hal ini tidak akan jadi
masalah serius di masa mendatang.
Kesimpulan
Teknologi sensor gambar masih terus berkembang, dari yang paling
mudah dilihat seperti kenaikan resolusi (megapiksel) hingga teknologi
lain yang bisa membuat hasil foto meningkat siginifkan. Yang saya
cermati adalah era Bayer sudah terlampau usang, dengan teknik
interpolasi yang banyak keterbatasan, perlu segera digantikan dengan
metoda lain. Sensor X Trans buatan Fuji membawa angin segar dengan
peningkatan kualitas foto dibanding sensor Bayer khususnya dalam hal
ketajaman dan kekayaan warna, namun sayangnya tidak (belum?) bisa
diadopsi di kamera lain. Sensor Foveon pun demikian, walau secara teknik
paling menyerupai emulsi film (yang artinya bakal memberi hasil foto
yang paling baik) justru dipakai di kamera yang jarang dijumpai seperti
kamera Sigma. Sensor kamera yang paling ideal itu harus cukup banyak
piksel (detail), punya dynamic range lebih lebar dari sensor
yang ada saat ini, punya filter warna yang lebih baik dari Bayer CFA,
dan efisien (harga, performa, kinerja ISO tinggi dsb). Kira-kira kapan
ya sensor ideal ini bisa terwujud?
 Home
Home






















0 komentar:
Posting Komentar